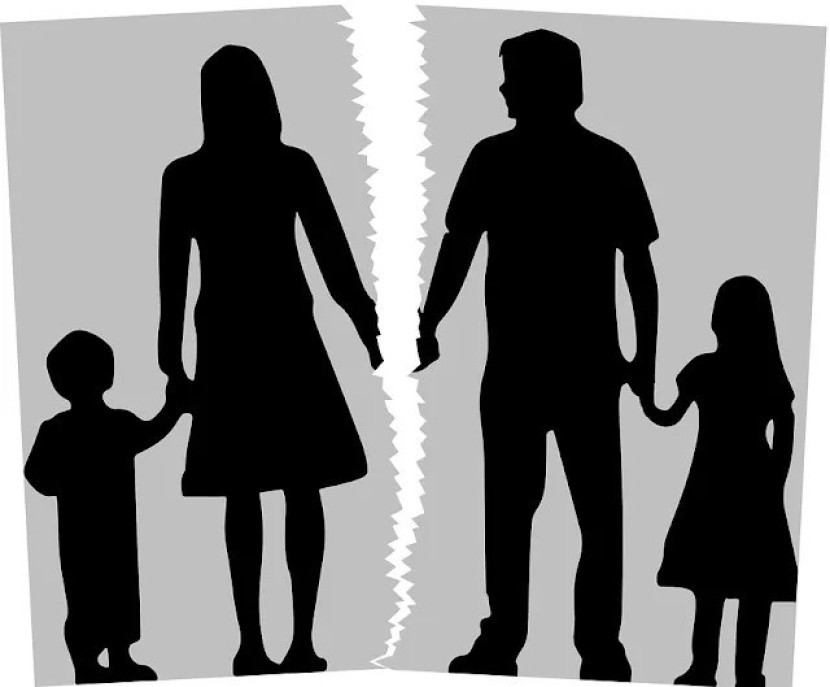Fenomena Penjarahan Rumah Pejabat: Sebuah Tinjauan dari Psikologi Sosial

Oleh Damar Pratama Yuwanto (Mahasiswa Psikologi Program Sarjana-Magister/Sarmag Universitas Gunadarma Depok)
Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada penjarahan rumah pejabat publik. Sejak Sabtu (30/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025), terjadi aksi penjarahan terhadap rumah-rumah yang diklaim milik sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach, serta rumah yang disebut milik Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Aksi ini terekam dalam berbagai video dan menyebar di media sosial. Awalnya massa hanya berniat melakukan aksi protes, namun situasi berubah menjadi penjarahan. Barang-barang seperti kursi, guci, peralatan elektronik, hingga barang koleksi pribadi ikut dijarah. Warga setempat dan petugas keamanan tidak mampu mencegah massa.
Penjarahan ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia, dipicu oleh kematian Affan Kurniawan (21 tahun), pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan polisi saat demo menolak kenaikan tunjangan DPR. Kerusuhan juga terjadi di berbagai kota, termasuk pembakaran gedung DPRD dan jatuhnya korban jiwa.
Aksi ini bukan sekadar ekspresi kemarahan spontan, melainkan cerminan kompleks dari dinamika sosial, frustrasi kolektif, dan respons psikologis terhadap ketidakadilan sistemik. Dari sudut pandang psikologi sosial, terdapat beberapa teori yang dapat membantu kita memahami fenomena ini secara lebih mendalam.
1. Deindividuasi: Ketika Identitas Pribadi Luruh dalam Massa
Deindividuasi adalah kondisi ketika seseorang kehilangan rasa identitas dan tanggung jawab personal saat berada dalam kelompok besar. Dalam kerumunan demonstrasi, individu seringkali merasa anonim—tidak dikenali atau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini bisa memicu perilaku ekstrem, seperti kekerasan dan penjarahan, yang biasanya tidak akan dilakukan dalam situasi normal.
Orang-orang yang menjadi bagian dari kerumunan seringkali bertindak lebih sebagai bagian dari kelompok daripada sebagai individu. Kemampuan untuk berbaur dengan orang lain dapat mendorong seseorang untuk meniru tindakan orang lain di sekitarnya. Individualitas mereka pun memudar, dan dalam arti tertentu, mereka menjadi anonim.
Deindividuasi dapat terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan pengendalian diri, menyebabkan seseorang berperilaku berbeda dari biasanya, dan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Rasa marah terhadap pejabat yang pamer dan menghina bisa memicu tindakan impulsif dan destruktif seperti perusakan dan penjarahan. Apalagi jika dipicu oleh postingan media sosial atau video viral pejabat yang menyakiti perasaan publik.
Psikolog forensik, John Delatorre, pernah menyatakan bahwa anonimitas memungkinkan seseorang melakukan perilaku yang tidak akan mereka lakukan jika dikenali. Menjadi anonim bisa membuka kesempatan untuk mewujudkan keinginan, melakukan perilaku yang selalu ingin mereka lakukan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai penghilang hambatan, yang memberi seseorang kebebasan untuk melepaskan kendali yang mereka alami sehari-hari.
Lantaran seseorang begitu asyik dengan apa yang dilakukan kelompok dan menjadi bagian darinya, kesadaran dirinya sendiri menurun. Mereka mengikuti arus, berapa pun jumlahnya.
Adapula kekuatan dan rasa aman dalam jumlah. Terkadang, melawan arus bisa terasa berbahaya atau berisiko. Bukan hal yang aneh bagi kita untuk tidak ingin terlalu menonjol. Ketika massa bertindak, batas moral individu bisa memudar.
2. Konformitas dan Tekanan Sosial: Ikut-ikutan karena Dorongan Kelompok
Konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Konformitas bisa pula suatu bentuk pengaruh sosial yang individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
Muzafer Sherif, tokoh psikologi sosial, melakukan eksperimen konformitas dengan menggunakan efek autokinetik, dimana peserta diminta memperkirakan pergerakan titik cahaya statis dalam kegelapan. Awalnya, perkiraan individu bervariasi, tetapi saat berdiskusi dalam kelompok, peserta mengembangkan norma kelompok bersama tentang seberapa jauh cahaya bergerak, yang menunjukkan konformitas informasional karena kurangnya referensi objektif.
Dalam situasi penuh tekanan dan ketidakpastian, individu cenderung mengikuti perilaku kelompok di sekitarnya. Ketika penjarahan dimulai oleh sebagian kecil demonstran, banyak orang lainnya bisa terdorong ikut serta, baik karena ingin diterima dalam kelompok maupun karena takut tertinggal.
“Kalau semua orang melakukannya, kenapa saya tidak?” menjadi narasi umum dalam situasi seperti ini.
3. Ketidakadilan Sosial dan Deprivasi Relatif
Teori deprivasi relatif menyatakan bahwa rasa ketidakadilan muncul bukan hanya karena kekurangan absolut, tetapi karena perbandingan sosial. Ketika masyarakat melihat pejabat hidup mewah hasil dari praktik korupsi, sementara mereka sendiri kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, rasa marah dan kecewa pun meledak.
Jika rakyat melihat pejabat hidup mewah, pamer kekayaan, dan tidak empati, mereka merasa semakin terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil. Perasaan "kami menderita, mereka malah sombong" menciptakan kesenjangan emosional yang tajam.
Ketika perasaan ini memuncak, bisa memicu amarah kolektif yang kemudian berubah menjadi kerusuhan, unjuk rasa, atau penjarahan sebagai bentuk pelampiasan atau perlawanan.
Penjarahan dalam konteks ini dipandang bukan sekadar kriminalitas, tetapi sebagai bentuk klaim keadilan yang tidak tersalurkan.
4. Frustrasi dan Agresi Kolektif
Model frustrasi-agresi menjelaskan bahwa frustrasi yang tidak memiliki saluran penyaluran yang sehat bisa berubah menjadi agresi. Dalam masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak didengar atau direspons, agresi bisa meledak dalam bentuk kekerasan terhadap simbol-simbol kekuasaan, seperti rumah pejabat.
Ketika masyarakat mengalami frustrasi karena kemiskinan, ketidakadilan, dan sikap arogan pejabat, agresi bisa diarahkan kepada simbol kekuasaan dan kemewahan. Penjarahan bisa dilihat sebagai bentuk pembalasan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.
5. Identitas Sosial dan Konflik Antar-Kelompok
Melalui kacamata teori identitas sosial, demonstran memposisikan diri sebagai "rakyat tertindas", sementara pejabat dilihat sebagai "penindas". Dalam konflik antar-kelompok ini, penjarahan bukan sekadar tindakan ekonomi, tapi juga simbol perlawanan, pergeseran kekuasaan, dan pernyataan identitas.
Dalam perspektif psikologi sosial dan filsafat politik, perilaku pejabat yang suka memamerkan kekayaan serta merendahkan kesusahan rakyat dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kontrak sosial. Konsep kontrak sosial sendiri merupakan gagasan dasar yang menjelaskan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.
Dalam kontrak ini, rakyat bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya dan menaati hukum, dengan imbalan bahwa pemerintah bertugas melindungi hak-hak rakyat, menjamin keadilan, dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bersama. Gagasan ini dikembangkan oleh para filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke.
Namun, ketika seorang pejabat publik justru bertindak arogan, mempertontonkan kemewahan hidup di tengah penderitaan rakyat, dan menunjukkan sikap tidak empatik, maka ia secara tidak langsung telah mengkhianati amanah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dalam bahasa kontrak sosial, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan moral dan sosial yang mendasari keberlangsungan sebuah negara atau pemerintahan.
Pelanggaran semacam ini memiliki dampak psikologis dan sosial yang luas. Dalam psikologi sosial, tindakan tersebut dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan frustrasi di kalangan masyarakat.
Teori ketidakadilan sosial (relative deprivation) menjelaskan bahwa kemarahan kolektif seringkali muncul bukan karena kemiskinan itu sendiri, melainkan karena rakyat merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan kelompok lain—dalam hal ini, para pejabat yang hidup mewah tanpa empati. Ketika ketimpangan ini ditunjukkan secara terang-terangan melalui perilaku pamer kekuasaan, maka rasa tersingkir dan amarah masyarakat akan semakin tajam.
Lebih jauh lagi, teori identitas sosial menjelaskan bahwa perilaku pejabat seperti itu akan memperkuat pemisahan antara kelompok "kami rakyat" dan "mereka elite penguasa". Ketika kelompok yang berkuasa dianggap tidak lagi mewakili nilai dan kepentingan rakyat, legitimasi mereka pun tergerus. Ketika hal ini terjadi, rasa solidaritas dalam masyarakat bisa berubah menjadi permusuhan terhadap simbol-simbol kekuasaan, termasuk institusi pemerintah, fasilitas publik, bahkan properti milik pejabat.
Teori frustrasi-agresi dalam psikologi juga menunjukkan bahwa frustrasi yang mendalam dan berkepanjangan seringkali berujung pada tindakan agresif. Dalam konteks ini, penjarahan atau kerusuhan bisa menjadi bentuk pelampiasan amarah terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat bukan hanya persoalan etika pribadi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan legitimasi politik. Ketika para pemimpin melanggar kontrak sosial dengan bertindak sewenang-wenang atau menghina kondisi rakyat, mereka turut menciptakan kondisi psikologis yang memungkinkan munculnya kerusuhan sosial, perlawanan sipil, bahkan revolusi.
Dalam sistem demokratis, kontrak sosial adalah fondasi utama kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Jika kepercayaan ini dihancurkan oleh arogansi dan ketidakpedulian, maka konsekuensinya bisa sangat serius dan merusak tatanan masyarakat secara luas.
Tentu, memahami fenomena ini dari sudut pandang psikologi sosial bukan berarti membenarkan tindakan kekerasan atau penjarahan. Namun, pendekatan ini membantu kita melihat akar masalah secara lebih luas, bukan hanya dari permukaan hukum semata.
Solusi jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar pengamanan—diperlukan keadilan sosial, transparansi, dan dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan itu, potensi ledakan sosial di masa depan bisa diminimalisasikan.
Depok, 31 Agustus 2025