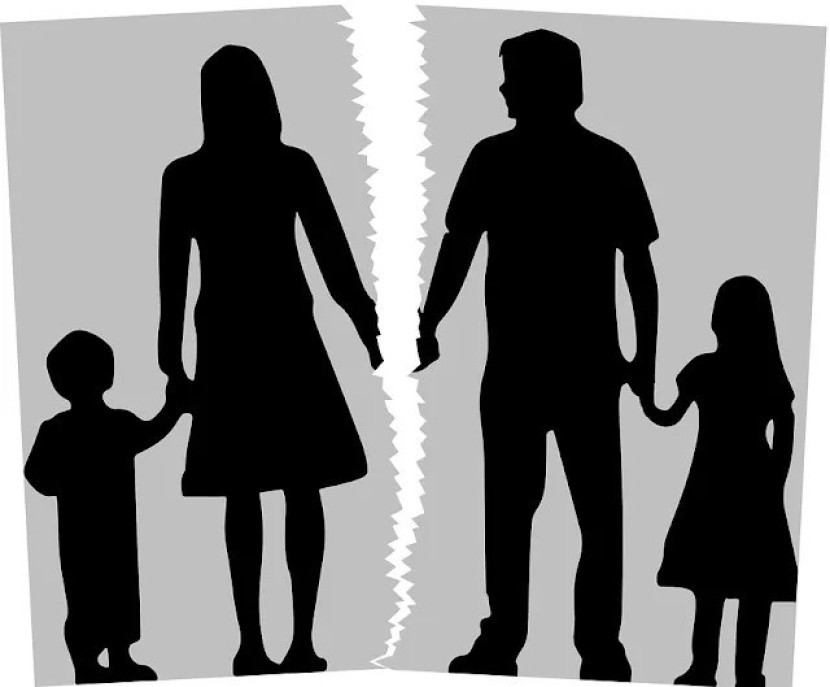Fenomena Rojali dan Rohana: Bukan Sekadar 'Irit', tapi Soal Harga Diri dan Citra Sosial

Oleh Damar Pratama Yuwanto (Mahasiswa Psikologi Program Sarjana-Magister/Sarmag Universitas Gunadarma Depok)
Akhir-akhir ini media sosial (medsos) diramaikan dengan dua istilah baru: Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya). Istilah ini muncul untuk menggambarkan perilaku pengunjung pusat perbelanjaan (mal) yang datang hanya untuk lihat-lihat, bertanya-tanya, berfoto, atau sekadar nongkrong, tanpa melakukan transaksi pembelian.
Di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli, Rojali dan Rohana menjadi gambaran nyata dari bagaimana masyarakat merespons keterbatasan finansial secara psikologis dan sosial.
Fenomena ini sering dianggap sekadar “gaya hidup irit” atau “window shopping massal”. Tapi jika kita telaah lebih dalam, ada proses psikologis yang kompleks di balik perilaku ini. Setidaknya, ada dua pendekatan psikologi yang bisa menjelaskan: mekanisme pertahanan ego dan konsumsi simbolik.
Menurut Bapak Psikoanalisis asal Austria, Sigmund Freud, manusia memiliki mekanisme bawah sadar yang disebut defense mechanisms untuk menjaga stabilitas psikologis ketika menghadapi tekanan, rasa malu, atau konflik batin.
Ketika seseorang datang ke mal, tertarik dengan barang-barang, tapi sadar tidak mampu membeli, maka muncul perasaan tidak nyaman (inferior, malu, kecewa). Untuk mengatasi perasaan ini, muncullah perilaku kompensatif seperti:
- Bertanya-tanya seolah ingin beli, padahal tidak.
- Coba-coba barang (tester, fitting room) untuk “merasakan” sensasi belanja.
- Berpura-pura sibuk melihat-lihat agar tidak terlihat “tidak mampu”.
Kini, bahkan berada di mal saja sudah cukup untuk "tampil" sebagai bagian dari kelas konsumen. Terlebih di era medsos seperti nongkrong di kafe agar bisa diunggah sebagai konten.
Ini disebut rationalization atau compensation, dua bentuk mekanisme pertahanan ego yang membuat kita tetap merasa baik-baik saja, meski tidak bisa memenuhi keinginan.
Kompensasi merupakan mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang menonjolkan kelebihan di satu bidang untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan yang dirasakan di bidang lain. Konsep ini awalnya dikemukakan oleh psikolog asal Austria Alfred Adler yang menyatakan bahwa dorongan untuk mengatasi inferioritas bisa menghasilkan pertumbuhan positif, seperti peningkatan motivasi dan citra diri.
Namun, kompensasi juga bisa berdampak negatif jika dilakukan secara berlebihan atau tidak disadari. Seperti menghambat pengembangan diri, terlalu fokus pada kekurangan, hingga tak bisa mengembangkan kelebihan atau menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, terlalu mementingkan diri sendiri. Kompensasi berlebih dapat muncul dalam bentuk usaha keras untuk menutupi rasa tidak aman, sementara kompensasi kurang bisa menyebabkan ketergantungan pada orang lain atau penghindaran masalah.
Contoh dari kompensasi bisa ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti olahraga, hubungan, kesehatan, dan pekerjaan. Untuk mengatasi kompensasi yang maladaptif, seseorang perlu melakukan introspeksi, mencatat pola perilaku, mencari dukungan dari orang terdekat atau profesional, dan membangun kebiasaan serta tujuan yang sehat secara emosional.
Dalam teori konsumsi simbolik, psikologi sosial melihat bahwa membeli barang bukan hanya tentang kebutuhan, tapi juga tentang identitas, status, dan simbol sosial.
Konsumsi yang bertujuan memberi sinyal tentang status sosial, keanggotaan kelompok, atau harga diri merupakan suatu aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Pengeluaran seperti itu terjadi bukan karena kegunaan fungsional barang, melainkan karena nilai simbolik yang diakui bersama secara sosial. Agar konsumsi dapat menjalankan fungsi simbolik ini, harus ada semacam koordinasi sosial – baik tersirat maupun eksplisit – mengenai simbol apa yang dianggap sah.
Berbeda dengan konsumsi biasa yang lebih menekankan pada kegunaan teknologi produk, dalam konsumsi simbolik, aspek teknis barang menjadi sekunder. Yang utama adalah bahwa barang tersebut disepakati memiliki makna simbolik yang dapat dikenali, baik untuk menunjukkan status, identitas kelompok, ataupun mempertahankan citra diri.
Dinamika konsumsi tidak bisa hanya dijelaskan oleh inovasi teknologi produk; melainkan perlu juga memahami motivasi psikologis dan sosial dari konsumen.
Dalam kenyataannya, banyak keputusan konsumsi dipengaruhi oleh keinginan individu untuk diakui secara sosial, menegaskan identitas kelompok, atau memperkuat harga diri. Untuk itu, proses pembelajaran sosial-kognitif di dalam kelompok memegang peranan penting dalam menyamakan cara pandang dan interpretasi simbol-simbol.
Simbol-simbol konsumsi ini bisa muncul, bertahan, atau hilang tergantung pada koordinasi perilaku di antara pelaku konsumsi serta pengaruh eksternal seperti iklan, yang membantu mempertahankan fokus perhatian konsumen pada simbol-simbol tertentu. Pada akhirnya, konsumsi simbolik dipandang sebagai medium komunikasi yang menyoroti pentingnya memahami motivasi atas perilaku konsumsi dalam menjelaskan evolusi pola konsumsi masyarakat.
Berfoto di depan toko brand mahal bisa menaikkan “kelas” digital. Merekam video aesthetic di mal memberi impresi gaya hidup tertentu. Artinya, orang tak perlu belanja sungguhan untuk mendapatkan "nilai simbolik" dari aktivitas belanja.
Fenomena Rojali dan Rohana pun mencerminkan realitas sosial-psikologis.
Masyarakat menyesuaikan diri secara mental terhadap tekanan ekonomi. Mereka tetap ingin menjadi bagian dari budaya konsumsi, meski secara ekonomi tidak mampu. Perilaku ini menjadi semacam "kompromi identitas" antara ingin tampil mapan dan kenyataan finansial yang ketat.
Rojali dan Rohana bukan sekadar sindiran gaya hidup. Mereka adalah simbol dari dinamika sosial dan psikologis masyarakat modern yang terus berjuang mempertahankan harga diri dan identitas sosial di tengah tantangan ekonomi.
Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bentuk resiliensi mental--orang masih mencari hiburan, tetap bersosialisasi, dan berusaha terlihat "baik-baik saja". Di sisi lain, ini bisa menjadi alarm sosial akan kesenjangan yang semakin terasa di ruang publik.
Depok, 3 Agustus 2025